Paradoks Prabowo: Indonesia “Paling Bahagia” di Tengah Keterpurukan PISA dan IQ
Wacana mengenai arah masa depan Indonesia sering kali terjebak dalam retorika optimisme yang melambung tinggi. Di panggung-panggung formal, narasi tentang “Indonesia Emas 2045” kerap digaungkan sebagai janji manis bahwa bangsa ini akan menjadi kekuatan besar dunia. Namun, di balik jargon tersebut, terdapat jurang pemisah yang lebar antara citra yang ingin dibangun dengan realitas kualitas sumber daya manusia yang sesungguhnya di lapangan.
Baru-baru ini, diskursus publik kembali menghangat menyusul pernyataan Prabowo Subianto yang mengeklaim bahwa masyarakat Indonesia adalah warga paling bahagia di dunia. Pernyataan ini memicu perdebatan sengit: apakah kebahagiaan tersebut merupakan tanda kesejahteraan yang hakiki, ataukah sekadar mekanisme pertahanan diri masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup? Di tengah klaim tersebut, terdapat data-data krusial yang justru menunjukkan kondisi yang kontradiktif.
Media sosial belakangan ini riuh menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat Indonesia sebagai warga paling bahagia di dunia. Warganet meresponsnya dengan beragam komentar jenaka sekaligus getir, karena merasa pernyataan tersebut kontras dengan realitas lapangan.
Ironi di Balik Peringkat PISA Di tengah klaim kebahagiaan tersebut, ada rapor merah yang luput dari perhatian. Peringkat PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia dalam hal literasi, numerasi, dan sains berada di level yang memprihatinkan. Sayangnya, kita nyaris tidak pernah mendengar Prabowo memberikan komentar mendalam atau solusi konkret atas masalah ini.

Padahal, kemampuan membaca dan berhitung adalah fondasi ilmu pengetahuan. Banyak fakta menunjukkan siswa tingkat menengah bahkan masih kesulitan membaca teks sederhana atau melakukan perhitungan dasar. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan masa depan bangsa ini akan rapuh. Apakah data krusial ini tidak sampai ke telinga sang Presiden?
Rendahnya IQ dan Masalah Sistemik Pendidikan Data rata-rata IQ nasional yang berada di angka 78 juga menjadi sinyal bahaya. Meski IQ adalah atribut personal, rata-rata nasional menggambarkan kualitas sumber daya manusia secara umum. Jika literasi rendah dan IQ jalan di tempat, posisi bangsa ini dalam kompetisi global kian terancam.
Persoalan ini berakar pada sistem pendidikan kita yang terjebak dalam siklus “ganti menteri, ganti kebijakan”. Perubahan hanya terjadi di permukaan—istilah dan sampul buku—tanpa menyentuh substansi peningkatan kemampuan siswa. Pakar pendidikan yang kritis sering kali dikesampingkan, kalah oleh kepentingan politik dan proyek strategis yang lebih berorientasi pada anggaran ketimbang mutu.
Budaya Akademik yang Semu Selain kurikulum, hambatan kemajuan kita adalah budaya. Budaya ewuh pakewuh membuat kritik terhadap atasan dianggap tabu, sementara disiplin waktu masih dianggap remeh. Di sisi lain, orientasi pendidikan kita masih pada gelar, bukan kompetensi. Hal ini menyuburkan praktik jasa pembuatan skripsi hingga ijazah instan. Kita terlalu fokus pada hal-hal artifisial, sementara kedalaman ilmu diabaikan.
Sistem pendidikan yang amburadul memerlukan pembenahan total, bukan sekadar pergantian nama. Jika Prabowo hanya mendengar laporan yang “menyenangkan” tanpa mau melihat fakta-fakta pahit seperti rendahnya literasi dan kualitas SDM, maka masa depan bangsa ini dalam bahaya. Masalah tidak akan pernah selesai jika sang pemimpin bahkan tidak menyadari bahwa masalah itu ada.
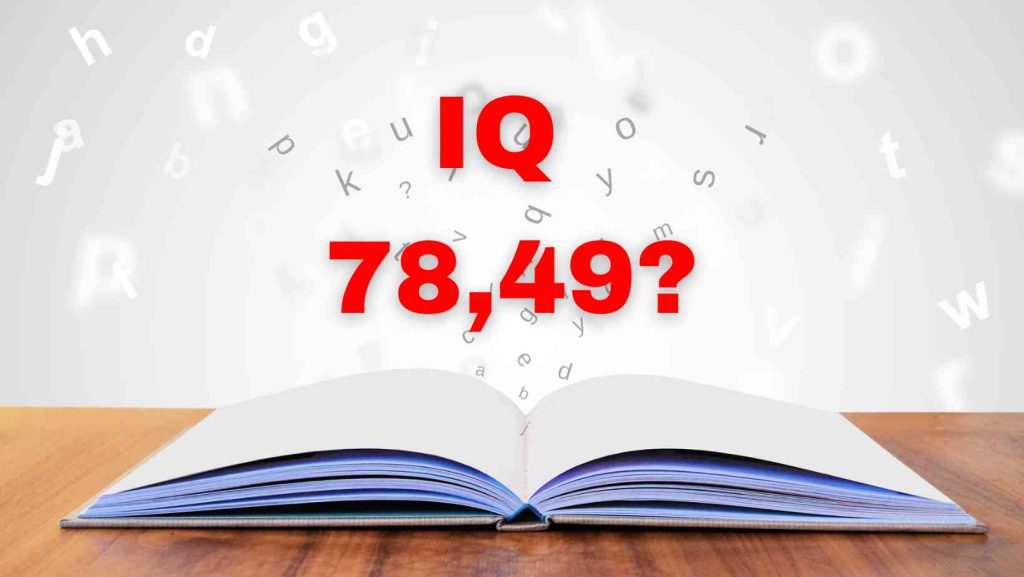
Menghadapi Fakta Pahit Membangun bangsa tidak bisa hanya bermodalkan narasi kebahagiaan yang semu atau laporan-laporan yang menyenangkan telinga pemimpin semata. Jika pemerintah terus-menerus menutup mata terhadap borok di dunia pendidikan dan rendahnya kualitas literasi, maka klaim kebahagiaan tersebut hanyalah topeng di atas kerapuhan sistemik. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang berani mengakui kekurangan dan bekerja keras memperbaiki akar masalah, bukan yang sekadar merayakan angka-angka yang bias.
Salam Penuh Kasih
Susy Haryawan



